 |
| Kotasouvenir.com |
Setelah jembatan Suramadu dibuka, bersama beberapa teman, saya terlibat diskusi soal masa depan Madura. Dalam diskusi muncul bayangan buruk, bahwa tidak lama lagi tanah-tanah di Madura akan berpindah kepemilikan. Ternyata tak perlu menunggu lama. Bayangan itu nyata. Di depan wajah sendiri.
Inilah cerita "sukses" jembatan Suramadu. Sukses menarik Madura ke dalam gurita neoliberalisme ekonomi. Madura menjadi surga bagi sekelompok orang yang rakus luar biasa. Dan momentum itu makin kuat, bukan karena orang Madura manyambutnya, tetapi karena negara memaksakannya.
Karpet merah pun digelar untuk menyambut investor. Seiring jembatan Suramadu dibuka, negara mendirikan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS). BPWS yang diberi wewenang mendorong percepatan pembangunan di Madura jelas lebih menyuarakan kepentingan negara (pemerintah pusat) atau investor ketimbang warga Madura sendiri.
Maka Madura pun disulap biar lebih "kinclong" di mata investor. Jalan raya diperlebar. Akses melalui jalur pantura sejak dari Bangkalan-Pasongsongan diperluas. Pelabuhan lama direnovasi sementara pelabuhan baru dibuka, termasuk di daerah Pasean, dekat Pasongsongan. Dan jangan lupa, Bandara Trunojoyo di sebelah Timur kota Sumenep, dekat asta Waliyullah Kyai Ali, saat ini juga diperluas. Dengan begitu, lengkaplah Madura diserang dari 3 penjuru; darat, laut, dan udara.
Baru-baru ini Presiden Jokowi memangkas hingga 50% tarif tol Suramadu. Dalam pernyataannya, pemangkasan ini untuk mendorong investasi lebih "kenceng" ke Madura. Karena dalam evaluasi pemerintah, tarif tol yang mahal akan membebani biaya transportasi yang memberatkan investor untuk berinvestasi di Madura. Dengan banyaknya investasi, diharapkan perekonomian Madura makin bergairah, dan bisa membuka lapangan kerja bagi warga Madura.
Sumenep sebagai salah satu kabupaten terkaya di Madura dengan kekuatan APBD lebih 2 triliun di tahun 2016 dan sumber daya alam yang melimpah menjadi incaran investor atau pemodal besar, baik lokal maupun asing. Belum lagi potensi pariwisatanya, Salopeng, Badur, Lombang, Wisata Oksigen Giliyang, Gili Labak, dan kandungan migas yang melimpah menjadikan Sumenep makin seksi untuk dilirik investor. Di daratan maupun lepas pantai, migas seakan bantal yang menjadi alas orang Madura tidur.
Setahun lalu, di Sumenep diselenggarakan seminar nasional tentang migas yang dihadiri pengusaha nasional. Penempatan seminar nasional tentang migas di Sumenep bukan soal sederhana, tapi—meminjam istilah Pak Pandji Taufik, ketua PCNUSumenep telah menjadi etalase dimana investor dengan mudah bisa melihat "barang" yang mau "dibeli".
Tak cukup itu, belakangan ini masyarakat Sumenep banyak kehilangan “tana sangkol", sesuatu yang dahulu dianggap sebagai bukan sekadar "benda" atau "barang". Dalam kosmologi orang Madura, tana sangkol memiliki makna sakral. Hubungan orang Madura dengan tanahnya adalah sekaligus hubungan dengan para leluhurnya. Memperlakukan tana sangkol sembarangan termasuk menjualnya tanpa dibenarkan secara budaya adalah pelecehan terhadap para leluhur. Dalam derajat tertentu, pelecehan itu diyakini bisa mendatangkan "tola" (marabahaya).
Kosmologi orang Madura tentang tana sangkol oleh kapital diiremukkan. Di atas tana sangkol telah berdiri bermacam infrastruktur kapitalisme, tempat sistem itu memulai gurita ekonominya dan memutar roda kapitalnya meski harus menghisap ribuan orang, termasuk pemilik tanah pada mulanya. Dan itulah yang akan terjadi nanti. Orang Madura cukup menjadi kuli di pulaunya sendiri.
Apakah massifnya penguasaan tanah belakangan ini oleh investor asing merupakan gambaran dari perubahan kosmologi orang Madura terhadap tana sangkol? Bisa jadi, iya. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan ada perselingkuhan penguasa dan pengusaha yang dengan otoritas dan hegemoninya "memaksa" masyarakat untuk melepas tanah. Di desa Lombang dan Lapa Daja, untuk menyebut kasus, penguasaan tanah melibatkan kalebun, mantan camat, serta para broker lokal yang setia pada investor. Dengan segala bujuk rayu, intrik, hingga "pemaksaan" ditempuh agar masyarakat melepaskan tanahnya.
Di sini saya melihat, kosmologi tentang tana sangkol hari ini tidak berjejak. Tak menemukan pijakan. Kosmologi orang Madura tersudutkan oleh perselingkuhan kapital dan kekuasaan. Jadi, perubahannya karena desakan dari luar ketimbang friksi internal.
Memang, dalam kajian Madura bertebaran tesis, seolah orang Madura tidak memiliki hubungan emosional dengan tanah. Salah satunya, budayawan/sejarawan modernis Prof. Dr. Kuntowidjoyo. Dalam bukunya Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940, Kunto menjelaskan bahwa karakter desa di Madura yang bercorak scattered village dengan rumah yang berserakan dan jauh antara satu tetangga dengan lainnya telah membentuk karakter orang Madura menjadi lebih individual (individual centered). Inilah salah satu alasan kenapa di Madura tidak ada pemberontakan petani yang terorganisir seperti di Banten ketika masa penjajahan Belanda dahulu.
Ada lagi kajian dibanding masyarakat Jawa, orang Madura lebih gampang meninggalkan tanahnya karena itu orang Madura dulu banyak dimobilisasi sebagai tentara kerajaan atau pasukan Belanda yang dikenal sebagai Barisan. Berlanjut hingga masa berikutnya dan bahkan sekarang, fenomena perantauan Madura diyakini karena hubungan emosional terhadap tanah rendah.
Penjelasan banyak pengkaji Madura seperti di atas bagi saya sangat sumir. Tana sangkol dahulu sangat kuat. Sifatnya yang sacral, yang menjelaskan bagaimana hubungan emosional orang dengan tanahnya dan para leluhurnya, tidak digambarkan. Saya menduga banyaknya orang Madura yang dulu dijadikan pasukan kerajaan atau Belanda yang bisa dimobilisasi ke mana-mana atau fenomena perantauan berhubungan dengan ketimpangan struktur kepemilikan tanah dan murahnya harga produk pertanian. Tepatnya, permasalahan itu muncul lebih karena bersifat struktural.
Soal karakter desa di Madura yang bercorak scattered village—berbeda dengan Jawa yang bercorak nuclear village—sebagaimana tesisnya Kunto, ternyata baru memiliki kekuatan jika dibaca dalam konteks sekarang. Rumah-rumah yang berserakan di Madura yang tidak mewujud satu gugusan desa seperti di Jawa telah menyumbang sebagai pertahanan terhadap gencarnya "penjarahan" tanah belakangan ini. Seandainya corak desa berbentuk nuclear village, tentu akan lebih banyak dan lebih mudah lahan-lahan kosong dikuasai investor asing. Jika dulu Kunto menyebut corak desa yang scattered village tidak revolusioner, justru sekarang bisa dijadikan kekuatan revolusioner.
Meski saat ini Madura seperti terjual habis (sold out), gerakan sosial yang mengupayakan "penyelamatan" harus segera dilakukan. Kosmologi, tradisi, pandangan hidup, nilai-nilai Madura tidak cukup hidup di pikiran, tapi juga bumi untuk berjejak. Ketika Madura kembali dijarah dan dijajah, saatnya orang-orang pesantren keluar menggumulkan kepesantrenannya untuk menjaga kedaulatan tanah dan isi yang dikandungnya. Ayo, selamatkan madura, sekarang juga!






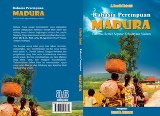
Posting Komentar